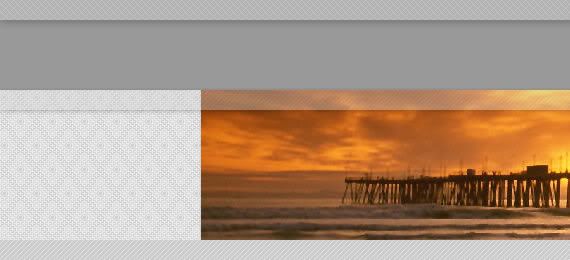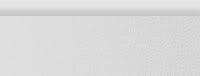| Sabtu, 29 September 2007 |
| SAJAK-SAJAK DIEN ZHURINDAH (TOPENG) |
Sumber : Riau Pos, 30 September 2007
TOPENG
1.
Dahulu engkau pernah berdongeng
tentang wajah-wajah topeng
yang bertubuh koreng dan berjiwa rombeng
Pernah juga kita berjalan-jalan
menyusuri bawah jembatan
dan engkau katakan:
”di sinilah makna kehidupan
lalu-lalang orang-orang kelaparan
berkeringat dahulu baru makan”
Sudah lama tak bertemu
semoga kita berpapasan di pintu waktu
2.
Berkelana aku membawa luka
mencarimu di hamparan senja
di bawah jembatan, aku buka kenangan
tapi jejakmu terhapus hujan
aku kehilangan
Ah-ya, kucoba saja mencarimu digemerlap malam
yang penuh riuh dengan orang-orang yang benci subuh
benarkan, bersua juga akhirnya
kusapa, kau seakan lupa
lalu kusodori kaca
praak, cerminnya retak
serpihan wajahmu berserak
Kukira hanya kau, ternyata pendongeng lainnya juga berkeliaran di lingkaran zaman, berbekal topeng-topeng yang di jual obral di sepanjang jalan
Pekanbaru, pagi bisu ‘07
NARASI PAGI
Malam merapat ke pagi
Langit memekat bintang pun mati
kubuka jendela
burung-burung hantu berpesta
berebut memagut aroma rangka
yang menyebar semerbak mekar kamboja
siapakah yang terluka
hingga isi langit berbelasungkawa
Nurani diterbangkan bayu
pagi mati di kamarku
Pekanbaru, pagi bisu ‘07
BIBIR PUISI
: Lelaki
Engkau menggaris pelangi
pada bibir tipis berduri
aku memasuki negeri mimpi
dan terjaga ketika rembulan pamit pergi
Pekanbaru, pagi bisu ‘07
SEKUFU
Kelak, jarak tak lagi mengoyak benak
kini kita terbenam di bungkam dendam
ketika gulana membangun istana bertahta luka
seperti opera yang harus diusaikan segera
kita berlomba memanipulasi cerita
bermain menjadi marhain
mengunyah remah
aku berada di kasta bawah
Sekufu…
bukankah Tuhan mencipta kita begitu?
Pekanbaru, pagi bisu ‘07
SEMENTARA
Berpisah saja
serupa teja dilupa senja
tak ada yang abadi dari kita
hanya tersisa sebaris nama
terukir di nisan penghias pusara
Pekanbaru, pagi bisu ‘07 |
posted by Komunitas Riak Siak @ 23.30  |
|
|
|
| Jumat, 28 September 2007 |
| Esai Sobirin Zaini [Kejujuran Berkarya ] |
Sumber: Riau Pos, 23 September 2007 Kejujuran Berkarya
dan Mempublikasikan Karya
Oleh Sobirin Zaini
Tak dapat dinafikan, jika sebagian penyair menganggap kerja kepenyariran adalah sebuah upaya membaca apapun dengan sepenuh kejujuran. Ketika persoalan atau kondisi lingkungan yang terjadi di sekitar diri penyair adalah sebuah kebusukan, misalnya, maka penyairlah yang akan menuangkannya sebagai sisi kebenaran dalam karyanya yang disebut puisi itu. Mungkin judul yang saya pilih di atas agak membingungkan. Karena pada kenyataannya justru apa pun yang coba ditulis seorang penyair memang adalah upaya untuk mengungkapkan secara jujur dan apa adanya seperti yang saya sebut di atas. Dalam hal ini, tentu, pembaca atau penikmat karya bernama puisi itu dituntut untuk selalu dapat memaknainya secara mendalam dan seksama, sehingga maksud dan pesan yang dituangkan penyair dalam karyanya dapat diterjemahkan ke dalam minda dan perasaan penikmatnya. Kita tahu, media cetak (dalam hal ini koran harian), dalam perkembangannya memang cukup memberi ruang untuk ikut melestarikan tradisi penulisan sastra lewat rutinitas halaman sastranya. Media cetak dalam format dan periode penerbitan lain seperti majalah, tabloid, buletin dan sebagainya juga memberi alternatif yang sama, disamping teknologi internet seperti sejumlah blog dan website yang menjamur di dunia maya. Kondisi ini pada akhirnya memang cukup membuat kita berbangga, karena dari sanalah tradisi penulisan sastra itu tetap berlangsung dan bahkan semakin menampakkan wujud perkembangannya. Tengok saja, tidak hanya "sastrawan-sastrawan tua" dengan publikasi luas karya mereka lewat media-media itu kian saja mengukuhkan eksistensinya, penulis atau sastrawan-sastrawan muda yang mengikuti jejak mereka juga akhirnya ikut dibesarkan dan diperhitungkan kehadirannya. Dan disinilah juga, peran redaktur yang mengurusi seputar tradisi penulisan sastra di media massa (dalam hal ini media cetak) itu mau tidak mau juga harus diperbincangkan. Karena tentu, ketika seorang penulis atau sastrawan mengirimkan karyanya pada sebuah media massa, orang yang pertama sekali membaca dan menyimak karya yang akan dipublikasi adalah redaktur sastra itu sendiri. Sehingga secara tak langsung, redakturlah yang mewakili masyarakat pembaca atau penikmat karya sastra itu sebelum jatuh ke tangan mereka. Dan disinilah kemudian, sejauhmana objektivitas penilaian redaktur terhadap karya sastra yang dipublikasikan juga kadang dipertanyakan, meski akhirnya yang menilai adalah pembacanya sendiri. Maka sangat mungkin, jika ternyata, karya yang telah dipilih dan dipublikasi itu belum tentu terbaik menurut pembaca dan penikmat sastra. Mungkin kita harus sepakat, jika ini bagaimanapun adalah sebuah otoritas redaktur yang dipercaya oleh jajaran redaksi medianya untuk membuat keputusan pada publikasi karya-karya itu. Sebagian penulis pun menganggap menulis dan berkarya itu sudah menjadi tugasnya, persoalan apakah akan dipublikasi atau tidak di satu media, itu bisa saja dipikirkan kemudian. Namun saya yakin, itu hanya di bibir saja, di hati kecilnya ia pasti berharap juga pada publikasi karyanya. Sampai ia kemudian harus pasrah dan "kalah sesaat" ketika ternyata redaktur sastra memutuskan untuk tidak memuat karyanya itu. Yang menjadi persoalan di sini––sesuai dengan maksud dari judul di atas---adalah bagaimana jika karya seorang penulis atau sastrawan itu terkesan sebagai sebuah upaya "mengelabui" pembacanya sehingga pembaca karyanya itu akhirya kecewa? Inilah yang sempat merisaukan saya ketika beberapa waktu lalu mendapatkan itu di sebuah media cetak (koran harian) yang cukup luas pembacanya dan selama ini dianggap mampu membantu memasyarakatkan tradisi penulisan itu. Secara tak sengaja (meski sebelumnya memang sengaja), saya membaca sebuah karya puisi yang sama dari seorang penyair yang disuguhkan pada edisi berbeda, namun telah dirubah dan coba dikoreksi oleh penyairnya sendiri. Judul puisi yang diterbitkan itu sama, tapi beberapa larik yang ada sudah bertambah dan berubah letaknya. Saya tidak tahu, apakah ini sebuah kesengajaan redakturnya sehingga puisi yang sama itu bisa dipublikasi dua kali meski pada edisi berbeda. Sementara tanda-tanda yang mengisyaratkan kesengajaan redaktur itu tidak ada. Apakah puisi yang terkesan tak selesai itu lebih penting dari setumpuk karya-karya dari sejumlah penulis atau sastrawan lain? Apakah ini adalah sesuatu hal yang wajar di dunia penulisan sastra koran kita? Sekali lagi, saya memang tidak dapat menjawab ini secara pasti. Karena saya juga bukan krtitikus sastra yang tahu bagaimana layaknya sebuah karya puisi yang proporsional itu. Hanya saja, hal ini tentu telah membuat penulis atau sastrawan lain yang kebetulan menunggu (karena mungkin kebetulan juga mengirimkan karyanya ke media itu) kecewa. Penikmat dan peminat karya sastra juga jadi bertanya-tanya, kenapa karya itu dimuat kembali tanpa ada catatan dari redaksi? Sementara kita tahu, periode penerbitan dua atau tiga bulan, belum tentu mampu menghapus memori mereka (pembaca) tentang apa yang pernah dibaca dan dinikmatinya. Apalagi kemudian mereka ternyata sempat mengkliping karya-karya itu. Disinilah, lagi-lagi, tanggung jawab seorang redaktur dipertanyakan kembali. Karena saya khawatir, ini adalah dampak kurangnya kejelian dan kecuaiannya, sehingga membuat media cetak bersangkutan terkesan sebagai tempat publikasi karya yang tergesa dari penyair yang coba mengelabui itu. Saya tahu, koreksi dan revisi karya memang sesuatu hal yang wajar bagi penulis atau sastrawan sendiri, tapi apakah pembaca mau menerima hal ini jika koreksi dan revisi karya yang sama itu dimuat berkali-kali? Karena pembaca sastra di sebuah media cetak (koran harian) tentu, selalu menginginkan karya-karya terbaru dan lebih bermutu. Sekali lagi, saya memang tidak menafikan bahwa koreksi dan penyuntingan kembali pada sebuah karya sastra oleh pengarangya adalah sesuatu hal yang wajar. Namun pertanyaannya, apakah redaktur sastra di sebuah media (koran harian) dapat memberi perlakuan yang sama untuk semua penulis atau sastrawan lain yang juga mengirimkan karyanya? Mungkin, saya pikir, ada baiknya, koreksi dan penyuntingan itu dilakukan secara intens sebelum karya tersebut dipublikasikan. Atau jika memang karya yang telah direvisi itu ingin dimuat kembali, redaktur paling tidak membuat catatan kecil yang menjelaskan itu. Dan hal ini dapat dilakukan tentu, jika redaktur sastranya sendiri mau membuka diri untuk berkomunikasi dan berdiskusi, minimal memberikan konfirmasi tentang "nasib" karya yang pernah dikirimkan penulis atau sastrawan ke medianya. Saya khawatir, ini adalah persoalan sepele yang tidak begitu perlu dibesar-besarkan, namun saya pikir ini tidaklah perlu terjadi. Karena sekali lagi saya juga paham, kalau penyair yang coba "mengelabui" itu adalah penyair pemula––untuk tidak mau menyebut muda seperti saya––yang masih mencari-cari identitas karya lewat gaya pengucapan, eksplorasi bahasa, dan lainnya. Namun begitu, garisbawahilah bahwa kerja kepenyairan seperti yang saya sebut di awal tulisan ini adalah sebuah pekerjaan membaca apapun dengan sebuah kejujuran. Jika pekerjaan ini dalam prosesnya ternyata tidak dilakukan dengan kejujuran, bagaimana kita bisa menawarkan kejujuran-kejujuran itu? Penciptaan karya sastra, seperti juga penciptaan karya seni lainnya, kita semua tahu, memang memerlukan sebuah proses dan perenungan-perenungan yang dalam. Seperti yang pernah dikatakan Chairil Anwar ––yang saya kutip sebagian di sini––dalam sebuah prosanya; "kita mesti menimbang, memilih, mengupas dan kadang-kadang sama sekali membuang. Sudah itu baru mengumpulsatukan." Penulis atau sastrawan selayaknya memang harus "memeram" beberapa waktu untuk ia sendiri akui kehadiran dan wujud sebuah karyanya. Ia juga dituntut untuk mengoreksi dan merevisi secara intens sebelum terlanjur dipublikasi dan sampai ke tangan pembaca.*** |
posted by Komunitas Riak Siak @ 07.56  |
|
|
|
|
| Sajak-sajak Sobirin Zaini [Suatu Malam Engkau Bertanya] |
Sumber: Riau Mandiri, 23 September 2007 SUATU MALAM, KAU BERTANYA Suatu malam, kau bertanya, di mana tuhan?
kutunjukkan pada sebuah langit yang gelap, ketika
matahari hanya sebuah titik dan kubentangkan
sajadah lalu kuajarkan kau sujud
di situ tuhan. Tidak, jawabmu, tuhan ada di sini
di hatiku yang linglung mencari rambu-rambu seperti
linglung burung-burung mencari
mangsanya di tengah hutan belantara
seperti ombak, kau susunkan kalimat zikir hingga
berbaris menuju sebuah muara
suatu waktu, tuhan di sana
tidak jawabku, tuhan ada di mana-mana
Dan sesungguhnya, kau percayalah
syahadah sudah lama berlidah dalam mulutmu
iman berkarat dalam jantungmu
tapi benda-benda dan waktu yang
mengarahkanmu pada surga semu itu
juga sederet nama-nama dan gelar dari ritual-ritual itu
di sebuah kampung yang luka setelah
perang mencari kekuasaan
itulah tuhan, katamu
ya, tentu, aku setuju, jika ini hanya sebuah percakapan
tapi setan menyesatkanmu karena selalu ada di kepalamu
Suatu malam, kau bertanya, di mana tuhan?
jawabku, tuhan ada di hati kita
maka sujudlah dengan sepenuh makna 2007 KABUT SUBUH //1
Tak ada puisi seindah doa-doa yang
terucap ketika kabut subuh mulai mencair
desah suaramu di ujung sana seperti
api yang kupendam jauh di dasar mimpi
titik aku menemukan diri sendiri setelah
kehilangan hadir matahari jelang pagi
dan puisi yang sebenarnya kau ucapkan itu
doa-doaku sebelum waktu benar membunuhku
//2
Engkaukah bunga yang kusemai itu?
kupetik suatu waktu ketika takdir
menentukan begitu dan tak menentu di hatiku
atau hanya akan layu kutingggal lagi tak berakar
lalu terkubur dalam tanah yang paling dasar
kalau begitu, inikah takdir dan garis tangan itu?
aku bukan kumbang yang akan menemanimu
sepanjang mekar kelopakmu
//3
Tunggulah kematianku, kepergianku
dalam catatan langkah perjalanan ini
sepanjang ini
untuk berat kuucap selamat tinggal
selamat tinggal
2007 |
posted by Komunitas Riak Siak @ 07.54  |
|
|
|
|
| Sajak-sajak M Badri [Elegi Para Petani] |
| Sumber: Majalah Sagang, September 2007
ELEGI PARA PETANI
kepada matahari, juga burung-burung kucangkulkan imaji
di bukit-bukit, sungai, dan ngarai. ladang-ladang begitu sunyi
menunggui ilalang dan kemarau menyanyikan puisi
kidung musim panen di pematang seperti suara detak jam
yang membisikiku jalan pulang
sebatang kalimat, mulai bertunas dan menggeliat
gabah melepuh di gudang-gudang, setelah kapal dagang
menaburkan beras dari negara tetangga
yang menggarami sawah-sawah
melukai lambung petani di kampungnya yang kerontang
anak-anak mengairi kata-kata
di balik tumpukan jerami, rerimbun masa depan
yang menjelma sedu sedan, sebab musim hujan
menenggelamkan harapan-harapan
bangku sekolah, dinding-dinding kemelaratan
sampai roda pedati menjadi begitu menyayat
bulan basah oleh keringat, berhulu di bukit tempat petani
menabuh gendang dan kembang kemiskinan
di sawah-sawah yang ditumbuhi elegi
juga cerita tentang gubuk-gubuk renta, beratap gulma
akhirnya puisi juga yang tumbuh dan menguning
hingga musim panen tiba, musim orang-orang memetik airmata
di pematang dan ladang-ladang pembantaian
yang memenggal rencana dan impian
Bogor, 2006
BUKIT BATU dari lembah aku melihat tubuhmu dikerumuni pepohonan
dengan akar-akarnya yang menancap di jurang kecantikan
tak ada retakan, apalagi reruntuhan yang menggelinding serupa jerawat
dan siulan burung-burung semakin menyembulkan dua biji mahkota
yang tumbuh setiap matahari terbenam. setiap makan malam
menghidangkan secangkir ciuman paling dalam
sampai menyisakan kenangan di langit dan jalan setapak
yang menuntunku ke jurang paling apak
sebuah tingkungan, tanpa tanda dan rerambu menebarkan
aroma tubuhmu: kembang kenanga dan hasrat purba
di kilometer-kilometer yang kulalui dengan puisi
paling sunyi. hingga nafas keheningan menjadi deru angin
menghantarkan sorot matamu ke lembah-lembah tempatku
mengabadikan resah. hingga musim hujan semakin menenggelamkan
wajahmu ke celah bebatuan
aku akan kembali menemukan dirimu, sendirian
ribuan tahun kemudian, setelah bereinkarnasi menjadi burung-burung
yang memagut serpihan masa lalu. aku tahu, kau pasti akan menenggelamkan paruhku di celah-celah bukit itu, sambil menagih janji
yang terlanjur terucap seperti sumpah para datu
Bogor, 2006 JALAN PANJANG kulihat sorot matamu lebih redup dari lampu-lampu yang berjajar menuju hulu
seperti sebuah lukisan panjang. terpajang di bantaran sungai, tempat gadis-gadis
metropolis mandi sambil menanggalkan selendang di tiang-tiang listrik
berharap jaka tarub mencurinya, hingga lupa jalan pulang ke negeri mimpi
yang berjarak dua tikungan dari pos ronda. tiba-tiba aku ingin mengabadikan malam
dalam telepon genggam, dalam ruang paling dalam.
tak perlu lagi mencurigai desir angin. atau mentertawai jejak kaki
yang terlanjur membekas di perempatan jalan, tempat engkau biasa menungguku
sambil menyumpahi segelas kopi. setiap pagi, setiap aku menjanjikan
puisi dan menyeruput madu yang meleleh dari pori-pori tubuhmu
sebelum kalender dengan angka-angka ganjil itu luruh
terbawa musim dingin yang membalut separuh wajahmu
di sebuah tanah lapang, yang memutar dan memanjang
debu-debu mengemasi ingatanmu: tentang kampung halaman, musim banjir
juga aroma nostalgia sepanjang trotoar yang ditumbuhi penjual jagung bakar
sampai dering telepon menjadi sepi. seperti suara hujan di halaman pertama
kisah cinta yang tertunda. tanpa ikatan dan rencana-rencana
yang selalu memenjarakan setiap impian
jemarimu meremang, mengikuti irama tanjakan
dan sorot matamu membentur tebing-tebing penuh lukisan dari asap pembakaran
yang tersusun dengan rapi. serapi aku merahasiakan setiap pertemuan
hingga jalan panjang itu hanya menyisakan jelaga yang tersangkut
di tikungan tempat kau terakhir membakar sapu tangan
Bandung, 2006 PEREMPUAN YANG MENCINTAI LAUT
: erf dermaga 1
bidukmu terapung di celah senja yang merona
antara percikan ombak dan dayung, mengitari semenanjung
menembus angin pesisir di pulau-pulau anyir
oleh aroma ikan, wangi kehidupan
ah geliat tubuhmu serupa duyung berenang ke tepian
menjemput cintamu yang tertambat di pelabuhan
dermaga 2
kepada karang kau bercerita tentang kehidupan
di laut yang membiru oleh ikan-ikan dan terumbu
warna jala dan kemilau nelayan menggarami petang
dan di pesisir, anak-anak itu, menyusu pada asin perahu
yang berlayar dari pulau ke pulau, sampai ke laut paling dalam
menebar masa depan dan impian
dermaga 3
jangan menangis, katamu
sebab air mata akan menenggelamkan separuh daratan
menghapus isyarat cinta yang terukir di atas pasir
bermekaran sepanjang pantai, sampai ke ujung palung
dan di lautmu, aku mencoba memahami bahasa ombak
membaca kilau mutiara di dasarnya
Bogor, 2007 RAHASIA HUTAN aku semakin terperangkap dalam aromamu
yang berguguran di musim kemarau
terjerembab di mulut anggau, perut begu
membunuh purnama di semak-semak
yang terserak
di bukit kering aku mulai menandai
masa kecil yang hijau, serupa daun-daun
dan onak melilit tubuhku dengan hangat
sepanjang siang. sampai raungan gergaji
meninabobokan semua orang
angin tiba-tiba meniupkan luka
yang bersarang di pucuk pepohonan
menyimpan dendam dan nujuman
di rawa-rawa, gubuk-gubuk renta, hingga jalan setapak
menuju muara tempat menghanyutkan semua balak
anyir masa lalu menjelma kabut
setiap pergantian musim membakar almanak
serupa tungku tua di tanah lapang, memanggang
semua nasib dan impian. hingga membumbung tinggi
menjauh, jauh sekali...
Bogor, 2007 |
posted by Komunitas Riak Siak @ 07.49  |
|
|
|
| Minggu, 23 September 2007 |
| Sajak-sajak Dien Zhurindah [Adakah] |
Sumber: Riau Mandiri, 02 September 2007 ADAKAH
Adakah Engkau hadirkan mentari
ketika rinai hujan menidurkan egoku
dan aku terbangun duluan
sebelum Engkau menitipkan pada bayu
untuk menerbangkan imajiku
dimana Engkau tempatkan istana megah-Mu
sedangkan pondokku
telah dihiasi pucuk-pucuk ilalang
yang menumpuk di kaki kayuku yang melapuk
Adakah Engkau hadirkan bintang
ketika aku tak lagi memimpikan bulan
dan aku terjaga duluan
sebelum Engkau menitipkan pada bayu
untuk menerbangkan imajiku
dimana Engkau letakkan purnama-Mu
sedangkan pondokku hanya dihiasi kegelapan
karena pelita telah enggan jadi pajangan
Adakah Engkau hadirkan mentari
adakah Engkau hadirkan bintang
adakah?
sedangkan aku ingin
hanya Engkau yang menguasai imajiku Pekanbaru, pagi bisu ‘07
KEHILANGAN
Pecah lagi gelisah
ketika wajah pengusung seribu tingkah
yang pernah singgah
bergegas menyusun langkah
kubuang sajakah sepasang sepatu
yang sengaja kau tinggalkan di depan pintu
atau kubiarkan saja di situ
berdebu digauli zaman dan waktu
Terkadang pagi
aku masih saja menyeduh kopi
dari cangkir yang menjelma menjadi bibir
ah, aku menghela nafasmu
yang khas aroma cerutu
tergesa aku menuju pintu
sepasang sepatu pada posisi lalu
usang dan berdebu
Kunikmati rumah sepi penghuni
hanya ditemani sepasang sepatu tanpa kaki
barangkali, kini aku kehilangan makna lelaki
Pekanbaru, pagi bisu ‘07
WAJAH
Belajar melukis, aku hanya mampu mencipta garis-garis
padahal aku ingin menggambar wajahmu
memberi rona pada lekuk yang sempurna
hingga kanvas usang
bernilai dan indah dipandang
Terkantuk-kantuk, tapi aku harus terus duduk
detik-detik kutahan, agar pelan-pelan berjalan
lukisan ini masih setengah badan
padahal ulang tahunmu bulan depan
Akhirnya lukisan wajahmu selesai juga
agar utuh kutambahi tubuh
sebentar, aku harus menukar warna latar
ku ingat, kau berkhianat pada hitam pekat
dan memilih mendidihkan putih
Wah…
ulang tahunmu meriah
sebagai hadiah kuberi lukisan wajah
ah maaf, wajahmu salah
aku tak teliti
telah menggambar wajahku sendiri
Janganlah marah, bukankah kita biasa bertukar wajah? Pekanbaru, pagi bisu ‘07 |
posted by Komunitas Riak Siak @ 01.05  |
|
|
|
| Kamis, 20 September 2007 |
| Sajak Tamu [Romi Zarman, Padang] |
bunga gelas berharap pada kelopak tapi kau gugurkan bunga.
apa yang kau petik itu yang kau tanam. kumpulkan tiup
kumpulkan peniup. kau dengar tanda tinggal rasa
dalam dada. dalam kelopak, adakah
yang sama dengan ia selain usia? berharap pada daun tapi kau patahkan tampuk.
apa yang kau gapai itu yang kau tuai. kumpulkan kulit
kumpulkan pengulit. kau lihat kata tinggal dusta
dalam rupa. dalam daun, adakah
tahun yang sama menyimpan sari yang sama? berharap pada sari tapi kau belah biji.
apa yang kau genggam itu yang kau pendam.
kumpulkan lirih kumpulkan pelirih. kau rasa kaca
tinggal cahaya dalam suara. dalam sari, adakah
yang tumbuh menunas di sana? ah, bunga. dalam gelas
batang terkurung cabang lepas (2007)
Baca Selengkapnya...
|
posted by Komunitas Riak Siak @ 23.41  |
|
|
|
| Kamis, 06 September 2007 |
| Sajak-sajak Sobirin Zaini [Sengak Tanahmu] |
Sumber: Majalah Sagang, September 2007
Sengak Tanahmu [1] Seperempat malam, sebelum kusadapkan rindu pada sebuah mimpi buruk tentang angin masa lalu, bau kelambu, karat tempayan dan remah bunga senduduk, telah kugenapkan jarak itu pada bulir-bulir pahit yang tergenang di matamu. Aku bergumam sepanjang malam karena aku durhaka, tak pernah menyisipkan kabar lewat doa-doa yang tak jelas ujungnya. Aku tahu, ini sebuah hikayat tentang biduk yang terbakar, tentang tenggelamnya perahu kertas yang kurangkai di lembah itu. Ketika kulihat bulan masih sabit, dan langit masih menggumpalkan awan dari sudut ke sudut yang lain. Tapi, bukankah sengak tanahmu itu juga yang memaksaku berlutut, lalu mengabutkan mataku dengan bulir-bulir batu waktu dari ujung lambungku? Cerita ini takkan pernah selesai. Jika hujan tetap mengkabarkan jua tentang harapan dan luka di jantungmu. Mungkin lebih baik aku pergi, dari tanah yang tak pernah kita petakan sebelumnya ini. Karena garis tangan begitu kentara, lukiskan kecemasan dan keruh arah perjalanan itu sendiri. Aku memang selalu tak tahu pasti! Pekanbaru, 2007 Sengak Tanahmu [2] Bermula dari sebuah percakapan. Aku berdiam dalam dendam dan meluruskan kaki di gubuk ini. Setakat begitu, namun tetaplah hamparan tanah dan rambut putihmu jua yang membayang. Ini renyah waktu dan gemulai dedaun rindu yang menggodamu. Ikatlah, pada pergelangan tangan tepat di detak nadimu, kau kuharapkan kembali dengan seribu perahu dan peta yang jelas, bukan barisan cerita dari sejumlah sobekan kertas. Di lain waktu, aku tahu, kau memang menunggu. Tapi bukankah waktu tetap sembilu yang kian menusukku? Pekanbaru, 2007 Sengak Tanahmu [3] Dan dengarlah, dengar dengan seluruh kemampuanmu mendengar; gemuruh sesayup angin yang lepas dari napasku. Buih-buih masa lalu membeku jadi batu. Dan batu meremukkan jantungku! Simaklah, simak dengan seluruh kemampuanmu menyimak, bahwa sebaris saja cerita dari malamku yang hampa, adalah butir keringatku mengapus catatan dosa-dosa. Dan maafkanlah, jika aku terpaksa jua meneriakkan satu saja keputus-asaan itu: aku kalah! Aku kalah!* Pekanbaru, 2007 *Sepenggal sajak Iyut Fitra Sengak Tanahmu [4] Tumpang tindih dan berkait-kelindanlah segalanya. Ada luka, hujan tak terduga, tawa hampa. Di sini, di tanah para boneka, aku kian memilih diam. Atau bicara dengan bahasa kelelawar, burung lelayang, ilalang tua. Lalu berjalan telusuri malam dengan arah yang tak pernah terbaca. Tak pernah. Karena sekali lagi, menundukkan pedang dalam sebuah peperangan waktu, aku butuh serdadu, atau hulubalang yang tangguh memegang gagang kerismu. Tapi, semua hanya cerita. Cerita tentang Dedap atau Terubuk setelah kita habis membakar tempurung dan anyaman tikar yang belum usai. Di tanah yang selalu terburai dengan pantainya yang tak lagi landai. Pekanbaru, 2007 |
posted by Komunitas Riak Siak @ 02.26  |
|
|
|
| Selasa, 04 September 2007 |
| Esai M Badri (Komunitas Sastra) |
Sumber: Riau Pos, 2 September 2007
Komunitas Sastra: Antara Mobilisasi Karya dan Mobilisasi Massa
Oleh M Badri Pertumbuhan komunitas sastra merupakan fenomena menarik untuk melihat perkembangan minat masyarakat terhadap sastra. Meskipun tanpa komunitas, sebenarnya sastrawan juga dapat berkembang. Tapi mengambil filosofi “sapu lidi”, dengan berkomunitas para peminat dan pegiat sastra dapat memperkuat individu, proses, dan karyanya. Sebab banyak hal didapat dari komunitas yang iklim di dalamnya cukup sehat untuk berkreativitas. Tanpa kepentingan-kepentingan tertentu selain bersastra (menulis, diskusi, apresiasi).
Ketika membaca beberapa tulisan, kadang juga mengamati langsung, saya melihat masih banyak yang belum memahami esensi dari sebuah komunitas. Meskipun komunitas adalah sekumpulan orang-orang, bukan berarti komunitas sastra merupakan ajang pengumpulan orang sebanyak-banyaknya dalam sebuah lingkaran kata: sastra, penulis, pena, dan sebagainya. Terlebih bila pengumpulan orang-orang tanpa melihat motif dan tujuan berkomunitas, apakah ingin berproses kreatif, sekadar meramaikan, atau menebar kepentingan (tertentu).
Apa arti sebuah komunitas sastra, bila orang-orang di dalamnya kebanyakan tidak mempunyai motivasi untuk berkarya? Saya memandang ini lebih kepada makna berkomunitas. Sebab hasil akhir dari para peminat sastra (terutama penulis pemula) adalah menghasilkan karya, bukan sekadar seremonial belaka. Bila sebuah komunitas sastra tak mampu menunjukkan karyanya, komunitas tersebut tak lebih dari mobilisasi massa.
Dalam pandangan saya, penggambaran tentang komunitas sastra bisa sangat sederhana, misalnya beberapa orang berkumpul pada suatu siang di galeri buku, atau suatu malam di bawah kolong jembatan. Dengan beberapa gelas kopi dan sebungkus rokok ––bungkusan gorengan juga barangkali. Membawa beragam ide dan pikiran untuk didiskusikan atau ditumpahkan. Bisa juga sangat wah, seperti di sebuah ruangan hotel dengan suasana yang serba mewah. Anggotanya juga mencapai puluhan orang dengan beragam latar belakang dan motif berkomunitas yang dibawa masing-masing individu.
Dari beberapa kali berkomunikasi dengan rekan-rekan penulis yang berkomunitas, saya kemudian memandang komunitas menjadi lebih simpel lagi: mengobrol dan menulis. Kadang hanya di kamar sempit berbau apak, di warung kopi sederhana, di toko buku kecil, di ruang maya, juga di ruang terbuka dan selalu berpindah-pindah. Tetapi para pegiatnya menampakkan eksistensinya, dengan menampilkan karya kreatifnya di sejumlah media massa. Menunjukkan kemampuannya melalui berbagai sayembara.
Namun bagaimanapun bentuknya, tentunya komunitas sastra merupakan sekumpulan orang yang tahu (atau ingin tahu) tentang sastra dengan melibatkan diri pada berbagai aktivitas sastra. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh pegiat komunitas sastra, dari diskusi ringan sampai perdebatan sengit tentang kesusastraan. Kadang hanya sekadar menggosip tentang individu-individu sastrawan atau menjadi ajang “pengujian” karya sebelum dikirimkan ke media massa, untuk mendapat pengakuan publik melalui perantara redaktur budaya.
Di sinilah kemudian muncul pertanyaan sederhana tadi, apakah komunitas sastra merupakan forum untuk memobilisasi karya atau memobilisasi massa? Kalau saya berpendapat, tidak ada yang lebih penting dari sebuah komunitas sastra selain memobilisasi karya dengan menulis dan menghasilkan karya-karya kreatif. Sedangkan mobilisasi massa, biarlah itu dilakukan ormas-ormas yang jumlahnya tentu jauh lebih banyak dari jumlah komunitas sastra. Tapi kalau kedua-duanya bisa digabungkan tentu suatu prestasi tersendiri ––atau masalah sendiri. Sebagai gambaran, misalnya sebuah komunitas penulis di suatu tempat jumlah pengurusnya diasumsikan sepuluh persen dari jumlah anggota. Bisa dibayangkan bila jumlah pengurusnya saja mencapai puluhan orang, berapa banyak karya yang dihasilkan (seandainya motifnya untuk berkarya) para anggotanya.
Keberadaan komunitas sastra memang sangat berpengaruh terhadap proses kreatif anggotanya. Karena biasanya dalam komunitas terjadi persinggungan kreatif, saling belajar, saling kritik dan sebagainya. Melalui proses tersebut kemudian akan lahir karya-karya yang bernas, penulis yang diperhitungkan, dan lebih penting lagi tetap terjaganya gairah untuk berkarya. Tetapi, kadang keberadaan komunitas sastra hanya menguntungkan individu-individu tertentu, tokoh-tokoh tertentu, semisal ketuanya atau donaturnya. Kalau yang terakhir ini, sebuah komunitas cenderung menjadi “alat” orang-orang yang berkepentingan, bukan menjadi “forum” bersama untuk berproses kreatif.
Karena komunitas sastra tidak sama dengan ormas, tentunya tujuan dari komunitas sastra adalah bagaimana sukses bersama dalam berkarya. Sehingga publik sastra tidak teracuni oleh ideologi-ideologi tertentu di luar konteks sastra yang membawa bendera sastra. Sebab dalam sastra sendiri telah terjadi kecenderungan pengkotak-kotakan, antara moralis dan liberalis, kanan dan kiri, dan sebagainya. Hal itu menyebabkan timbulnya sekat-sekat, pertentangan yang mengarah pada permusuhan, bukan malah memunculkan perdebatan yang sehat untuk menemukan muara sastra yang universal. Apa jadinya bila kepentingan di luar sastra (terlebih tidak memahami sastra) turut ambil bagian dalam polemik tersebut.
Esensi Komunitas
Kalau ditanya apakah yang dibutuhkan publik sastra dari komunitas, jumlah karya atau anggotanya? Saya yakin, dengan akal sehat, semua akan sepakat karya lebih penting dari orang-orangnya. Bahkan seringkali publik mengenal karyanya daripada penulisnya. Itulah realitas dari dunia tulis-menulis, dunia sastra dengan segala warnanya. Bahwa tidak ada yang lebih penting dari karya. Hal ini juga diakui oleh sastrawan sekaliber Joni Ariadinata beberapa waktu lalu, dalam suatu perbincangan sastra di Pekanbaru. Pengakuan legalitas organisasi (seperti SK dan atribut) tidak penting bagi penulis, tetapi yang penting karya apa yang telah dihasilkan. Itulah perbedaan komunitas penulis dengan ormas.
Kesuksesan komunitas juga tidak ditentukan oleh figur tokohnya, nama besar organisasinya, terlebih kekuatan dananya. Sehingga pandangan tentang pentingnya faktor sastrawan seniornya, penyandang dana, campur tangan pemerintah, kemampuan lobi untuk menyukseskan acara seremonial, dalam sebuah komunitas hanyalah pemikiran sempit (juga picik). Dalam publik sastra yang menjadi ukuran keberhasilan adalah kualitas karya yang dihasilkan anggota komunitasnya.
Di sini yang sering dilupakan adalah bahwa keberhasilan aktivitas kesastraan tergantung bagaimana masing-masing pribadi berproses kreatif untuk menghasilkan karya. Keberadaan komunitas hanya faktor pendukung dan penyemangat untuk terus berkarya. Sehingga percuma saja menempel di depan kebesaran nama komunitas kalau tidak berbuat apa-apa, tidak menghasilkan karya. Hanya pesta dan hura-hura. Sebab nama besar komunitas bukan menjadi jaminan kualitas karya anggotanya.
Dalam beberapa kali diskusi kadang saya heran terhadap sikap beberapa pegiat komunitas ––terutama pemula. Baru satu atau dua kali menulis sudah bisa mengukur kualitas karyanya ––tentunya dari sudut pandang pribadi dengan memakai jubah besar nama komunitas. Sehingga menggugat redaktur sastra koran atau majalah, kenapa tidak memuat karya-karyanya. Penilaian-penilaian individu seperti ini sebenarnya sah-sah saja, sepanjang untuk evaluasi terhadap karya yang telah dibuat. Bukan justru menjustifikasi bahwa karya yang telah dihasilkan sudah “luar biasa” sehingga wajib disiarkan kepada publik. Gugatan-gugatan narsisme seperti ini sebenarnya tidak perlu muncul seandainya penulis mau berkaca dengan membaca karya-karya penulis yang benar-benar luar biasa, lalu mengevaluasi karya sendiri. Bukan malah “buruk muka cermin dibelah”.
Masalah lain yang kadang timbul dalam komunitas sastra adalah munculnya virus epigon pada penulis pemula. Kecenderungan “mendewakan” sang senior atau sang guru menyebabkan keseragaman gaya penulisan. Dalam jangka pendek wajar bila murid menirukan gurunya, namun bila berkesinambungan dan menjadi indoktrinasi saya kira membawa masalah. Calon penulis tidak memiliki kebebasan menampilkan gaya atau tidak berani memunculkan karakter kepenulisannya. Inilah bila komunitas menjadi tempurung bagi katak kreativitas, bukan menjadi sungai yang mengalirkan kreativitas. Maka komunitas hanya akan kontraproduktif dan memandulkan proses kreatif anggotanya.
Esensi penting dalam berkomunitas adalah bagaimana individu-individu yang akan berkelompok membawa idealisme dan semangat masing-masing. Sebab komunitas hanya wahana untuk berkreasi, berinteraksi dan berekspresi. Dengan semangat dan idealisme, para pemula tidak terjebak pada bayang-bayang kebesaran komunitas, jumlah anggota komunitas, indoktrinasi komunitas, nama besar figur atau batas-batas kreativitas. Sehingga bisa memilih, menjadi idealis atau elitis. Maka pegiat komunitas sastra di Riau, berlomba-lombalah menghasilkan karya, bukan sekadar mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya.*** |
posted by Komunitas Riak Siak @ 06.12  |
|
|
|
|
| "riak siak riak kata/ mengalir ke muara karya/ imaji sedalam-dalamnya/ tak surut dilekang usia" |
| Logo |
|

|
| Tentang Riak Siak |
|
| Menu |
|
| Pelabuhan |
|
|
| Dermaga Deklarator |
|
| Pesan Tamu |
|
|
| Detak Siak |
|
|
| Penunggu Sungai |

|
| ***** |
template design by isnaini.com
 |
content design by negeribadri
| |